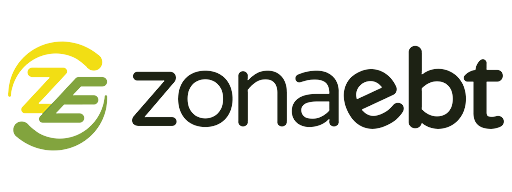- Istilah Fast fashion diperkenalkan pada 1990-an awal oleh kantor berita New York Times, sebagai bentuk kritik atas brand Zara yang menghasilkan produk tekstil hanya dalam 15 hari.
- Insdustri tekstil ini ternyata memiliki sisi gelap terutama dalam lingkungan seperti eksploitasi air tanah yang berlebih, hingga pencemaran air dari pewarna kimia, hingga serat kain dan mikroplastik.
- Laporan Departemen Tenaga Kerja AS tahun 2018 menemukan bukti adanya pekerja paksa dan pekerja anak di industri mode di Argentina, Bangladesh, Brasil, Tiongkok, India, Indonesia, Filipina, Turki, Vietnam, dan negara-negara lain. Bahkan perempuan muda umur 18 dan 24 tahun sering ditemui dalam industri ini.
- Slow fashion diharapkan dapat membantu praktik kebiasaan yang konsumtif terhadap fashion. World Resources Institute juga menyarankan para perusahaan besar harus mulai berinvestasi dalam model bisnis busana berkelanjutan ini dan memaksimalkan masa pakai produk mereka.
Penggunaan pakaian oleh setiap orang tentu akan terus berganti, baik karena kerusakan maupun sekadar keinginan mengikuti tren. Setidaknya, industri fesyen memproduksi sekitar 100 miliar pakaian setiap tahunnya. Jumlah ini meningkat dua kali lebih cepat dibandingkan awal tahun 2000-an.
Faktor “sekadar tertarik” inilah yang mendorong tingginya produksi industri pakaian sehingga memunculkan kekhawariran. Riset dari Earth.Org mengungkapkan bahwa lebih dari 92 juta ton pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah setiap tahun.
Industri fesyen hadir untuk memenuhi permintaan konsumen dengan memproduksi pakaian secara masif dan cepat demi keuntungan. Fenomena inilah yang kemudian dikenal dengan istilah fast fashion, sebagaimana digunakan oleh The New York Times.
Apa itu Fast Fashion?
Fashion, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai mode atau gaya busana, merupakan bentuk ekspresi diri yang diwujudkan melalui pakaian dan cara berpakaian yang populer serta diadaptasi oleh suatu budaya. Dahulu, mode sulit diakses oleh banyak orang karena proses pembuatannya memerlukan keterampilan menjahit dan bahan tekstil yang tidak murah. Hanya segelintir kalangan berada yang mampu memilikinya.
Namun, seiring berkembangnya industri, pakaian menjadi semakin mudah diproduksi berkat bantuan mesin. Hal ini memungkinkan mode dinikmati oleh lebih banyak orang dari berbagai kalangan.
Fast fashion awalnya merujuk pada produksi pakaian dalam jumlah besar dan harga murah yang meniru gaya peragaan busana serta menyesuaikan dengan tren terkini.
Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh The New York Times pada awal 1990-an ketika merek fesyen Zara mulai memasarkan produknya di New York. Misi Zara untuk merilis koleksi baru hanya dalam waktu 15 hari mendorong munculnya istilah fast fashion.
Keberhasilan Zara dalam merespons tren dengan cepat menginspirasi merek-merek besar lainnya seperti Shein, UNIQLO, Forever 21, dan H&M untuk menerapkan strategi serupa. Sayangnya, model produksi massal ini turut menyebabkan penumpukan limbah tekstil di tempat pembuangan akhir, yang banyak di antaranya tidak diolah kembali secara berkelanjutan.
Gelapnya Industri Fast Fashion

Produksi fesyen secara masif tentu meningkatkan kebutuhan akan bahan baku pembuatannya, seperti serat dan air. Laporan Quantis International tahun 2018 mengungkapkan bahwa produksi serat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan cadangan air tanah secara berkelanjutan.
Riset ini juga memaparkan setidaknya tiga faktor utama penyumbang polusi global dari industri tekstil. Pertama, proses pewarnaan dan penyempurnaan menyumbang 36% dari total polusi, diikuti oleh proses persiapan benang sebesar 28%, serta produksi serat yang menyumbang 15%.
Selain itu, penting untuk dicatat bahwa banyak serat yang digunakan saat ini merupakan serat berbasis plastik, yang dapat mencemari tanah dan perairan melalui partikel mikroplastik.
Menurut analisis dari Business Insider, industri fesyen menyumbang sekitar 10% dari total emisi karbon global, jumlah yang setara atau bahkan lebih besar, dibandingkan dengan total emisi yang dihasilkan oleh seluruh negara di Uni Eropa.
Baca Juga
Riset yang dilakukan oleh Chloe Lam dari Earth.Org mengungkap bahwa proses pewarnaan tekstil menggunakan bahan kimia pada kain menyumbang sekitar 3% emisi karbon dioksida (CO₂) global dan lebih dari 20% polusi air global. Angka ini belum termasuk emisi dari proses persiapan benang dan produksi serat, yang keduanya memiliki dampak signifikan terhadap penipisan sumber daya alam, karena memerlukan energi dalam jumlah besar—termasuk energi yang berasal dari bahan bakar fosil.
Dilansir dari Earth.Org (20 Januari 2025), pada tahun 2012, Zara mampu mendesain, memproduksi, dan mengirimkan pakaian baru hanya dalam dua minggu. Sementara itu, Forever 21 membutuhkan enam minggu, dan H&M sekitar delapan minggu. Pendatang baru dalam industri fesyen cepat, Shein salah satu perusahaan besar asal Tiongkok, bahkan dapat menghadirkan produk baru dalam waktu hanya 10 hari.
Bahkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) memproyeksikan adanya peningkatan besar-besaran dalam industri ini pada tahun 2030. Tren ini diperkirakan akan menyebabkan lonjakan signifikan dalam jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri tekstil.
Rentan Mengeksploitasi Para Pekerja
Meskipun kemajuan teknologi dan mesin telah meningkatkan efisiensi produksi, keterampilan manusia tetap sangat dibutuhkan dalam industri tekstil. Di perusahaan-perusahaan besar, sektor ini masih menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun, kondisi ini sering kali menjadikan kesejahteraan buruh semakin rentan.
Dalam bukunya No Logo, Naomi Klein menjelaskan bahwa banyak perusahaan tekstil besar memilih mendirikan pabrik di negara berkembang karena biaya tenaga kerja yang rendah, keringanan pajak, serta lemahnya regulasi ketenagakerjaan dan lingkungan. Salah satu contohnya adalah Tiongkok, di mana banyak merek ternama asal Amerika Serikat menempatkan proses produksinya karena peraturan lingkungan yang sering kali diabaikan.

Eksploitasi pekerja juga rentan terjadi, terutama terhadap pekerja perempuan. Laporan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada tahun 2018 menemukan bukti adanya praktik kerja paksa dan pekerja anak di industri fesyen di berbagai negara, seperti Argentina, Bangladesh, Brasil, Tiongkok, India, Indonesia, Filipina, Turki, Vietnam, dan sejumlah negara lainnya.
Mirisnya, menurut lembaga nirlaba Remake, sekitar 80% pakaian jadi diproduksi oleh perempuan muda berusia antara 18 hingga 24 tahun. Industri tekstil dan fesyen memang kerap lebih mementingkan penjualan dan laba dibandingkan dengan kesejahteraan para pekerjanya.
Peneliti Annie Radner Linden dalam penelitiannya yang berjudul An Analysis of the Fast Fashion Industry menilai bahwa industri fesyen merupakan sektor yang padat karya, padat modal, namun juga padat pekerja yang membuat isu perlindungan tenaga kerja menjadi semakin kompleks.
Apakah Slow dan Sustainable Fashion Solusi?
Slow fashion merupakan respons terhadap meluasnya tren fast fashion yang mendorong produksi tekstil secara berlebihan. Gerakan ini menekankan pentingnya mengurangi konsumsi, serta memprioritaskan pakaian yang berkelanjutan, baik dari segi bahan maupun proses produksinya yang ramah lingkungan.
Slow fashion diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan aspek kemanusiaan dalam industri fesyen. Secara global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah membentuk UN Alliance for Sustainable Fashion, sebuah aliansi yang bertujuan menghentikan praktik industri fesyen yang merusak lingkungan dan berdampak buruk secara sosial.
Indonesia sendiri sudah banyak start-up yang mengembangkan produk-produk ramah lingkungan yang bebas dari Greenwashing. Seperti contohnya brand Rentique yang menyediakan fashion rental dan resale, yang memungkinkan masyarakat untuk menyewa pakaian alih-alih membelinya.
Baca Juga
Salah satu contoh pelaku slow fashion di Indonesia adalah Pijak Bumi, sebuah merek alas kaki (footwear) yang menggunakan bahan-bahan daur ulang untuk produk-produknya. Beberapa material yang kerap mereka gunakan antara lain ban bekas, serat kelapa, dan katun.
Sementara itu, World Resources Institute (WRI) menyarankan agar perusahaan-perusahaan besar mulai berinvestasi dalam model bisnis fesyen berkelanjutan. Lembaga ini juga mendorong peningkatan kualitas produk agar tidak mudah rusak, serta mendesak perusahaan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para pekerja dalam rantai produksinya.
#zonaebt #sebarterbarukan #ebtheroes #KurangiPlastik #MengolahSampah #Mikroplastik
Editor : Alfidah Dara Mukti
Referensi
[1] The Environmental Impact of Fast Fashion, Explained
[2] 10 Concerning Fast Fashion Waste Statistics
[3] 4 reasons why fast fashion will never be green
[4]By the Numbers: The Economic, Social and Environmental Impacts of “Fast Fashion”
[5] 10 Brand Fashion Indonesia yang Mengusung Konsep Sustainable Fashion