
Sumber : https://pixabay.com/id/photos/matahari-terbenam-pabrik-bangunan-6226244/
- Mengetahui sejarah adanya konsep perdagangan karbon dunia dan urgensinya.
- Memberikan pengertian atau definisi dasar dari perdagangan karbon.
- Mendeskripsikan mekanisme dari dua jenis perdagangan karbon.
Saat ini dunia mengalami darurat ancaman permasalahan lingkungan, salah satunya adalah perubahan iklim ekstrim akibat dari peningkatan emisi gas karbon atau gas rumah kaca. Banyak aktivitas atau tindakan yang dilakukan baik oleh individu, kelompok bahkan suatu korporasi turut menyumbang peningkatan emisi gas karbon ini. Serangkaian tindakan tersebut dikenal sebagai jejak karbon, istilah yang mungkin sudah tidak asing didengar.
Adanya kegiatan industrialisasi menjadi salah satu penyebab peningkatan emisi gas karbon. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V), industrialisasi merupakan usaha mendorong perkembangan industri dalam suatu negara. Beberapa anggapan mengatakan bahwa proses industrialisasi merupakan salah satu solusi cepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, industrialisasi juga dipandang sebagai salah satu cara untuk menyelenggarakan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.
Namun, efek negatif bagi lingkungan tidak terhindarkan di antara gemerlapnya hasil yang didapat dari industrialisasi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa lingkungan banyak terdampak dari proses industrialisasi khususnya dalam hal pembukaan lahan. Contohnya, industri kelapa sawit yang mengalihkan fungsi hutan sebagai tempat industri. Meskipun berdampak positif bagi masyarakat sekitar, tapi kerusakan hutan yang ditimbulkan menjadi bayaran mahal untuk sektor industri tersebut. Pembukaan lahan hutan untuk industri dengan cara membakar lahan, meningkatkan jumlah gas karbon yang dilepaskan ke atmosfer bumi dan memperburuk perubahan iklim.
Akibatnya, konsentrasi gas rumah kaca atau gas karbon semakin tinggi yang membuat suhu bumi semakin panas. Tidak hanya itu, industrialisasi yang menggunakan energi listrik dalam jumlah besar juga berkontribusi terhadap pelepasan emisi gas karbon. Hal ini terutama terjadi jika sumber energi listrik tersebut berasal dari bahan bakar fosil, seperti pembakaran minyak bumi dan batu bara. Oleh karena ini banyak pihak yang melakukan inovasi guna mengurangi emisi gas karbon yang dihasilkan dari industrialisasi. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan penggunaan sistem perdagangan karbon.
Baca Juga:
Asal Mula Munculnya Sistem Perdagangan Karbon

Istilah perdagangan karbon mungkin masih kurang familiar di kalangan masyarakat. Namun, bukan berarti bahwa istilah ini menjadi hal baru di dunia apalagi dalam pembahasan isu lingkungan. Pada kenyataannya, konsep perdagangan karbon pertama kali diusulkan pada tahun 1997 dalam Protokol Kyoto. Protokol Kyoto merupakan suatu komitmen atau perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum, dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara global. Seperti yang dilansir oleh zonaebt.com pada Gaia.id, bahwa negara-negara industri yang termasuk dalam protokol Annex I (Lampiran I) diwajibkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka dan diberikan target penurunan yang spesifik.
Masih dari sumber yang sama, disebutkan bahwa Protokol Kyoto mengizinkan negara-negara industri yang masuk dalam protokol untuk mendapatkan kredit karbon melalui proyek-proyek pengurangan emisi yang dilaksanakan di negara lain. Berikut adalah 3 (tiga) macam mekanisme fleksibel perdagangan karbon menurut Gaia.id :
- Perdagangan Emisi (Emission Trading), antar negara Annex I yang memiliki kewajiban mengurangi emisi dapat berjual beli emisi gas rumah kaca.
- Implementasi Bersama (Join Implementation), memungkinkan beberapa negara Annex I melaksanakan proyek pengurangan emisi di negara lain dan mengklaim pengurangan emisi tersebut sebagai bagian dari upaya mereka.
- Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism), memungkinkan negara Annex I untuk mendukung proyek pengurangan emisi di negara-negara berkembang dan memperoleh kredit karbon sebagai kompensasi.
Namun demikian, perdagangan karbon internasional tidak serta merta dapat diterapkan setelah penandatanganan Protokol Kyoto. Konsep perdagangan karbon mulai aktif diterapkan pada tanggal 26 Februari 2005. Seebelumnya pada tahun 2001, Denmark menjadi negara yang secara sukarela menerapkan perdagangan karbon melalui Sistem CO2 Denmark.
Pengertian Sistem Perdagangan Karbon
Perlu diketahui perdagangan karbon, menurut voaindonesia.com yaitu jual-beli sertifikasi atau izin untuk menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 dalam jumlah tertentu. Dalam pengertian perdagangan karbon tersebut ada istilah kredit karbon (carbon credit) yaitu, sertifikasi atau izin pelepasan karbon. Selain itu, dikenal juga kuota emisi karbon (allowance). Satu kredit karbon sama dengan pengurungan atau penurunan emisi sebesar satu ton CO2. Emisi gas karbon disebabkan oleh beberapa hal seperti pembakaran bahan bakar fosil, kebakaran hutan dan pembusukan sampah.
Kemudian, pembeli karbon merupakan industri, perusahaan atau negara yang menghasilkan emisi gas karbon. Pihak-pihak tersebut merupakan subjek yang menghasilkan emisi gas karbon dalam jumlah yang besar, seperti penggunaan energi fosil yang tinggi dan lain sebagainya. Selanjutnya, penjual dalam sistem ini adalah perusahaan atau negara yang dalam kegiatannya mampu menyerap emisi gas karbon. Dapat dikatakan kegiatan yang mereka lakukan menghasilkan emisi karbon yang lebih sedikit. Kredit karbon tidak dapat dengan bebas diperjualbelikan. Oleh karena itu, sebelum diperdagangkan kredit karbon harus disertifikasi oleh badan yang berwenang.
Baca Juga:
Mekanisme Perdagangan Karbon

Ada 2 (dua) jenis perdagangan karbon yaitu perdagangan wajib (mandatory carbon market) dan perdagangan sukarela (voluntary carbon market). Selain itu, jika dilihat dari mekanisme penjualannya, perdagangan karbon dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perdagangan emisi dan perdagangan kredit karbon.
Pertama mengenai skema atau mekanisme perdagangan emisi, ini umumnya digunakan untuk pasar atau transaksi karbon yang sifatnya wajib atau mandatory carbon market. Unsur kewajiban ini muncul karena adanya pembatasan jumlah karbon yang diperdagangkan. Selanjutnya untuk partisipan pada mekanisme perdagangan ini adalah perusahaan, organisasi maupun negara.
Mengenai unsur kewajiban yang timbul dari pembatasan atau pengurangan emisi, diterapkan dalam bentuk allowance atau mengalokasikan kuota. Kemudian, bagi pihak yang terkena pembatasan emisi maka wajib untuk membuat laporan secara berkala mengenai emisi karbon yang dihasilkan. Pembuatan laporan ini ditujukan kepada lembaga terkait dalam skema perdagangan karbon. Dengan adanya laporan ini, maka perusahaan dapat memperkirakan berapa emisi karbon yang dapat dikeluarkan. Di akhir periode perdagangan, laporan tersebut akan diperiksa sehingga diketahui berapa emisi karbon yang dikeluarkan oleh setiap peserta.
Apabila ada dari peserta yang melewati ambang batas pengeluaran emisi karbon yang sudah ditentukan, maka perlu membeli allowance tambahan. Peserta dapat membeli allowance tersebut, kepada peserta yang memiliki kuota tidak terpakai atau emisi yang dikeluarkan tidak mencapai batas yang ditetapkan. Sebaliknya, peserta yang masih memiliki ‘sisa’ kuota dapat melakukan penjualan yang membutuhkan kuota tambahan. Berikutnya, mekanisme perdagangan kredit karbon atau juga dikenal sebagai sistem carbon offset atau baseline-and-crediting. Perlu diketahui bahwa pada mekanisme perdagangan karbon ini tidak mengenal sistem kuota atau allowance.
Sertifikasi dari penurunan gas karbon merupakan ‘objek’ dari mekanisme perdagangan karbon jenis ini. Di Indonesia, komoditas tersebut sering disebut sebagai kredit karbon, di mana setiap penurunan satu ton karbon dioksida maka akan mendapatkan satu unit kredit karbon. Pada mekanisme perdagangan ini nilai karbon yang didapatkan di akhir periode dapat dijual. Nilai karbon yang dijual itu digunakan oleh peserta lain untuk memenuhi target penurunan emisi yang juga disebut sebagai zero emission atau carbon neutral.
Editor : Alfidah Dara Mukti
Referensi:
[1] Sejarah Perdagangan Karbon
[2] Bisa Tekan Emisi, Begini Penjelasan Mekanisme Perdagangan Karbo
[3] Perdagangan Karbon: Pengertian, Manfaat, Cara Kerja, dan Dampak
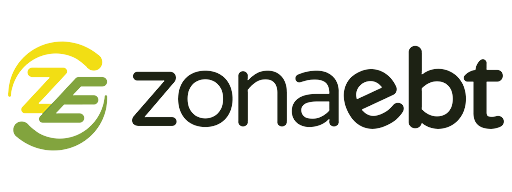





Comment closed